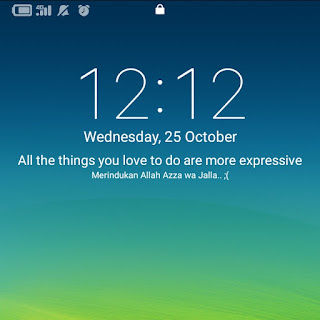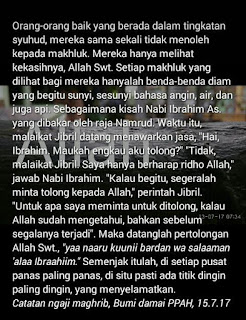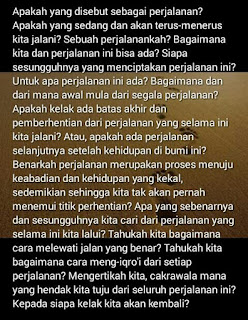Eufoni Samawi
Posted on October 11, 2010 by LMCR
Oleh: Mashdar Zainal
Di sana, di tempat-tempat itu selalu kulihat mereka. Mereka yang melewati titian hidup dengan nafas berat tersengal-sengal. Mereka yang selalu menapaki jejak demi rasa lapar yang tak pernah jinak. Mereka yang mengaburkan cinta demi dahaga yang terus melata.
Di sana, di tempat-tempat itu, selalu kulihat mereka…
Di persimpangan raya, di mana lampu merah gemar menyala, kulihat dua orang anak berparas baja, yang seorang menggamit luka di pangkal muka, yang satunya menimang balutan perban sepanjang lengan. Mereka berlomba-lomba memungut iba dari Sang Hidup yang barangkali dititiskan pada orang-orang yang matanya enak dipandang.
Pula di sana, di stasiun, gudang iblis berjibun, juga kulihat seorang lelaki tua yang tak memiliki kelopak mata. Maka, dua liang menganga di wajahnya. Pita suaranya seolah tak punya jeda untuk selalu berkamit serupa pawang peminta hujan, seolah lagu-lagu itu dapat menggiring mendung yang akan menghujankan koin-koin berkerak ke mangkuknya yang kerap berisi keluh kesah. Masih seperti yang lalu-lalu, ia digandeng perempuan gendut berbedak tebal yang setia, setia menuntun si buta, setia menguras tandas recehnya.
Tak lupa pula, di sana, di terminal, pondok si lugu menjadi bebal. Juga kujumpai lelaki baya berkaki pengkor. Ia menggelosor di kaki-kaki kursi tunggu penumpang, menjilati kaki-kaki bersepatu yang kemudian berdiri mengorek receh yang terselip dalam saku-saku mereka. Mulut itu acap kali menggumam do’a bagi siapa saja yang masih menganggapnya manusia.
Dan tentu saja, di alun-alun kota, panti si Sekar bermain mata, menawarkan tubuhnya yang beraroma lezat seperti pizza hangat. Di sana kusua juga, perempuan tua bermata tinta sebelah merah. Ia menimang bayi yang disulap jadi boneka. Ia mengambah setiap muka, memamerkan bayinya yang busung lapar, yang butuh beras untuk membaluti tulang. Mereka-mereka, kesemuanya itu, memiliki harapan yang sama untuk meneruskan novel kehidupan mereka.
Awalnya, aku hampir tak percaya waktu pertama kali memergoki kedatangan mereka. Aku melihat mereka datang pagi-pagi buta, saat dunia masih terkantuk-kantuk. Mereka datang diantar van mengkilat, serupa anak-anak sekolah dengan mobil jemputan yang istimewa. Mereka diturunkan satu persatu dari mobil mewah itu untuk menyelinap ke penjuru keramaian kota yang masih lengang melata. Di sana, para peminta-minta yang tuna itu akan menghabiskan hari, menggantungkan harapan mereka di bawah terik matahari yang tak punya belas kasihan. Mereka akan kembali dijemput malam nanti, jauh selepas isya’, saat jalan-jalan kembali menjadi sepi.
Sejujurnya pertanyaan di benakku berjibun-jibun. Kenapa hampir semua dari para pengemis itu tuna dan menyedihkan? Ataukah sengaja, ada orang yang mengoleksi makhluk-makhluk cacat itu untuk meraup rupiah? Memang cukup masuk akal, koin receh itu akan mudah tumpah oleh wajah-wajah mereka yang miris. Semakin menyedihkan, semakin menguntungkan. Begitulah yang ada dalam syakwa dugaku. Meski begitu, aku tak pernah ingin tahu lebih banyak tentang mereka. Bagiku, receh-receh yang sering kuletakkan pelan-pelan ke tangan-tangan dan mangkuk-mangkuk mereka sudah mewakili kepedulianku.
Selain di tempat-tempat di mana iblis suka menjelma menjadi manusia, masih ada satu tempat lagi yang belum kusebutkan, tempat yang dekat dengan sesuatu yang tenang; di pintu gerbang sebuah masjid—inilah yang sebenarnya hendak kuceritakan.
Di sana, di tepian gerbang masjid raya, setiap usai sholat Jum’at sampai bedug maghrib gagah tertambat, aku selalu melihat gadis kecil itu. Gadis tujuh tahun berwajah rembulan, dengan kerlingan mata yang bagai menyimpan sebuah dunia. Dunia yang penuh dengan kupu-kupu.
Gadis kecil itu selalu duduk di tepian gerbang. Rambutnya yang kusam tertutup kerudung tipis yang suka terbang digoda angin. Ia duduk bersila beralas kardus, kedua tangannya mencengkram erat nampan bambu yang berisi tahu goreng dan cabai hijau.
Setiap bedug maghrib bertalu, gadis kecil itu selau tampak terburu-buru, mengucap salam lalu hilang di jemput perawan malam. Setiap wajah rembulan itu pergi, rembulan di langit tak pernah sabar untuk menggantikanya. Seolah ia setia berdiam di pucuk kubah dan tak mau enyah menggantikan posisi gadis kecil itu.
Namun sungguh, hatiku gelisah. Sudah tiga Jum’at aku tak lagi melihat gadis kecil berwajah terang itu. Ke manakah gerangan dia? Apakah dia sudah tidak berjualan lagi? Ataukah dia sedang sakit? Perlukah aku menyisir rumah-rumah kardus sepanjang tepi sungai yang pernah ia ceritakan, untuk menjumpainya kembali? Ah, aku merindui gadis kecil itu. Merindui suaranya yang merdu, yang suka menyayikan lagu-lagu berbahasa Arab. Merindui rembulan jernih dan kupu-kupu di matanya yang kerap membuatku menyendiri, memaknai hidup.
“Tahu…! Tahu…! Kak tahu, Kak…!” aku teringat kata-katanya yang polos, “Kalau kakak mau membeli tahu buatan amak saya ini, saya akan menyanyikan sebuah lagu buat kakak.” Itulah kali pertama aku menatap matanya yang jernih yang di dalamnya terasa hidup berjuta kupu-kupu adi warna. Maka, aku tak bisa menjelaskan mengapa aku tergoda untuk menghampiri gadis mungil itu.
“Benarkah?” aku menghampirinya.”Nama kamu siapa?”
Ia tersenyum,”Anjum!”
“Anjum? Anjum saja?” tanyaku lagi.
“Anjum Basyariah!” Balasnya tersipu.
“Namamu bagus sekali. Dan benarkah, kamu mau menyayikan sebuah lagu buat kakak? Kau bisa menyanyi?”
”Tentu. Apa kakak bersedia membeli tahu buatan mamak saya ini?”
”Ya. Baiklah, kalau begitu kakak ambil tahu buatan mamak kamu itu. Sepuluh ya…!”
“Sepuluh Kak!?” ujarnya girang, matanya bertambah bening, memperjelas kupu-kupu yang menari di dalamnya.
“Iya, sepuluh!” Aku meyakinkannya. “Satunya berapa?” tanyaku kemudian.
“Lima ratus, Kak!” sahutnya,”Kalau kakak mengambil sepuluh… berarti saya harus menyanyikan sepuluh lagu dong, buat kakak!?” lanjutnya, tetap tersenyum.
“Memangnya harus begitu?” godaku.
Ia hanya menjawab dengan senyum, senyum yang tak pernah putus.
“Baiklah… Untuk kakak, kamu cukup menyanyikan satu lagu saja, tapi lagunya harus enak didengar. Bagaimana?” tawarku.
“Tentu!” jawabnya singkat.”Sekarang kakak simak, ya….!” beberapa detik kemudian matanya mulai terpejam, bibirnya mulai menggumam…
Hmm… Kam hasanat ladzatan lil mar’i qaatilatan… Min haitsu lam yadri annas suma fi dasami… Wahsya dasaisa min ju’in wa min syiba’in… Farubba mahmashotin syarum minat tukhomi…[1]
….Sudah berapa kali kelezatan membunuh manusia…., tanpa ia tahu, justru racun tersimpan dalam lezatnya hidangan. Maka… takutlah akan tipu daya dalam lapar dan kenyang, seringkali rasa lapar lebih buruk daripada kekenyangan…..
Subhanallah, aku merinding mendengarnya. Di antara deru bising kendaraan dan hiruk pikuk orang-orang yang menguing seperti kawanan kumbang sengat, lagu itu tersentil syahdu mendayu. Seolah menyirep suara-suara tak karuan yang membising. Dengan sangat perlahan, seolah ada sesuatu yang terbang menemui keindahan yang ada di langit.
Apakah gadis kecil itu paham dengan apa yang ia nyanyikan?
Subhanallah, suara gadis itu terlampau lembut, selembut sutera firdaus yang berkibar dihembus angin. Terkadang liukan suaranya yang meninggi, membuncah seperti seruling Daud di tengah malam. Aku terpejam mendengarkan lagu itu, membiarkan si gadis kecil menggamit jariku dan menuntunku menemui negeri hijau yang penuh dengan bambu-bambu kuning dan bunga-bunga rumput. Aku merasa menemukan dunia di atas langit, dunia yang penuh dengan puisi-puisi dan gesekan biola. Aku seperti menemukan sesuatu yang telah lama kurindukan, sesuatu yang memiliki altar berkilau di negeri malakut, sesuatu yang bersinggasana di atas awan. Ya, aku menemukanya, dalam lagu itu, dalam suara itu, dalam gadis kecil itu.
Aku serasa terbangun dari mimpi indah saat gadis kecil itu menepuk lenganku.
“Bagaimana, Kak, lagunya?” tanyanya.
Aku tergagap membuka mata setelah terdiam lama. Aku menatap kembali kupu-kupu di matanya, “Lagumu itu seperti lagu dari surga. Aku tak bisa mengungkapkanya.” Balasku.
“Benarkah? Lalu kenapa kakak memejamkan mata? Apa lagu saya membuat kakak mengantuk?”
“Untuk menghayati keindahan, terkadang mata kita memang harus terpejam. Kamu juga melakukanya. Kamu menyanyi sambil terpejam, kan?”
Lagi-lagi, gadis kecil itu tersenyum.
Sejak Jum’at itu, setiap Jum’at sore aku lebih banyak menghabiskan waktuku dengan gadis kecil itu, sampai senja merembang. Tak terasa, aku telah menjadi seorang pelanggan tetap sekaligus teman baik gadis itu. Rupanya gadis kecil itu tak sependiam yang kukira. Dari bibirnya yang tipis itu, ia kerap bercerita tentang banyak hal. Tentang rumah kardusnya yang berkali-kali larung setiap musim hujan tiba. Tentang bunga bakung yang tumbuh indah di keranjang sampah. Tentang kucingnya yang beranak lima dan berbelang sama.. Tentang ayahnya—yang kata mamaknya—telah lama merantau ke surga dan suka mengirimkan uang jajan setiap tanggal 10 Muharram. Tentang mamaknya yang suka menggoreng tahu dengan tirisan minyak bawang. Tentang adiknya yang berusia lima tahun, yang suka bermain balap kecoak. Juga tentang bintang berbentuk bunga yang setiap malam menjagai atap rumahnya dan mengajaknya bernyanyi. Dan masih banyak lagi.
“Kenapa kau hanya berjualan pada hari Jum’at saja?” tanyaku padanya suatu kali.
“Karena, supaya Anjum bisa menemui bapak di perantauanya, di surga.”
“Mengapa begitu?” selidikku.
“Karena, kata mamak, kalau Anjum pingin ketemu bapak, Anjum harus mau menuruti setiap kata-kata mamak.”
“Memangnya, mamak Anjum bilang apa saja?”
“Mamak bilang, kalau mau ketemu bapak, Anjum harus jadi anak yang jujur, rajin sholat, rajin ngaji, juga berbakti pada orang tua. Nah, selain hari Jum’at, Anjum harus ngaji, itu perintah mamak, Anjum tak boleh membangkang. Selagi Anjum ngaji, mamak berkeliling kampung menggendong adik, sambil teriak: ‘Tahu… Tahu….’, begitu…..” Ia tertawa lepas saat menirukan mamaknya berteriak menawarkan tahu dagangannya.
Sepertinya itu tawa lepasnya yang terakhir kali, yang masih kuingat. Beberapa Jum’at berikutnya ia tampak selalu murung, hinggga aku menemuinya yang terakhir kali, ia masih murung dan lebih pendiam. Setiap kali aku mendekatinya dan menanyakan apakah dia baik-baik saja, dia selalu mengangguk, anggukan yang tak kuyakini artinya.
“Baiklah, akan kuborong semua tahu yang kamu jajakan hari ini. Bagaimana?” ujarku lembut, berusaha mencari senyumnya yang hilang.
“Iya, Kak. Terima kasih.” Itu saja jawaban yang keluar dari bibir mungilnya.
“Apa kamu tidak ingin menyanyikan satu lagu pun, untuk kakak?” aku mencari perhatianya.
Ia mengangguk lesu. Setelah lama sekali, baru bibirnya bergerak. Namun sepertinya ia menyanyi hanya untuk dirinya sendiri.
Hmm…. Dunya laa tarham… Dunya laa tarham…
……Duhai dunia kau tidak berbelas asih padaku……
Lagu itu dibawanya dalam dayuan-dayuan dalam. Hingga lagu itu berakhir, aku mendapati setitik air dari matanya yang terjatuh pada nampan yang dipangkunya, titik itu luruh pula dan mengembang pada taplak meja merah pekat berbatik putih, yang ia lipat sebagai tutup nampan. Aku tak mampu berkata-kata lagi. Aku ingin membenamkan gadis kecil itu ke dalam dinding dadaku, tapi kemasygulan telah membuatku diam. Tanpa gerak, tanpa suara.
Itulah, terakhir kali aku menjumpainya, hingga beberapa hari berikutnya, aku mendengar kabar dari seorang bocah laki-laki yang menggantikannya berjualan di pintu gerbang masjid. Bocah laki-laki itu bilang bahwa Anjum dibawa ke Jakarta oleh temannya teman Almarhum bapaknya, kabarnya Anjum mau di sekolahkan di sana.
Setelah kejadian itu, rembulan yang biasa begadang di puncak kubah lebih sering bersembunyi di balik mendung, cahyanya meredup. Setelah kejadian itu pula, seusai sholat Jum’at aku tak lagi duduk berlama-lama di tepian gerbang masjid bersanding dengan gadis kecil penjual tahu. Aku lebih banyak berdiam diri di dalam masjid, terkadang sampai tertidur di sana.
Beberapa bulan tidak melihat rembulan dan kupu-kupu dalam wajah gadis kecil itu, rupanya kehidupanku masih bisa berjalan sebagaimana biasa, bahkan tak lebih buruk dari sebelumnya. Namun, lagu-lagu itu, seperti selalu mengiang di telingaku, memaksaku untuk membiasakan diri untuk bangun tengah malam, menyendiri di bibir balkon, menatap jentera langit, mencari bintang berbentuk bunga yang sering ia ceritakan. Hingga pada sebuah malam, aku bertemu Anjum dalam mimpiku.
Dalam mimpi itu hanya ada kami berdua, di sebuah oase di tengah padang gurun yang pasirnya kemuning bening seperti butiran madu beku. Tiba-tiba saja Anjum sudah berdiri di belakangku dengan menggenggam tongkat kecil panjang yang berkilauan. Ia menyanyikan sebuah lagu yang maha indah. Lagu yang paling indah yang pernah kudengar selama hidupku. Lagu yang sama sekali tidak beraroma lagu apa pun yang ada di dunia. Saat melantunkan lagu itu wajah Anjum sudah menjelma purnama penuh, suaranya jauh lebih merdu dari yang kudengar sebelumnya. Hanya saja…..
Hanya saja, aku mendapati kupu-kupu indah yang biasa menari di matanya terberangus kecoklatan, gersang, dan menjadi bangkai. Kelopak mata Anjum seperti terkelupas, lalu bola matanya menjadi bola pingpong kering yang meleleh, sama sekali tidak bergerak ataupun berkedip. Baru kusadari bahwa tongkat yang ia pegang telah menjadi matanya.
Ya Tuhan…, siapakah yang mengambil sinar mata itu?
Mulutku gagu, ragu, “Anjum…, penglihatanmu? Maksudku, apakah pengelihatanmu baik-baik saja?”
“Ouh, itu. Kakak tak usah khawatir, saya baik-baik saja.”
“Tapi…”
“Baiklah, supaya kakak tidak penasaran saya akan menceritakan semuanya” balasnya.
Aku masih tergugu, menunggu hikayat merdu yang hedak menyembul dari ujung lidahnya. Maka ketika rasa penasaranku menggumpal sampai ke ubun-ubun, Anjum pun mulai membuka mulutnya. Bagai seorang pendongeng ia meriwayatkan bahwa dirinya telah didatangi makhluk bermuka merah, bertanduk, dan berekor lancip seperti mata anak panah. Ia berujar bahwa makhluk itu datang karena terusik oleh kidung-kidung yang dinyanyikannya. Lantas, makluk itu marah dan meminta pita suaranya.
“Kalau makhluk itu meminta pita suaramu, mengapa sekarang kamu masih bisa bernyanyi? Bahkan suaramu lebih merdu.” Aku menanggapinya.
“Aku berhasil mengelabuhi makluk bodoh itu. Hik..hik…,” balasnya sambil cekikikan, “aku mengatakan pada makhluk itu bahwa yang menyanyikan lagu-lagu itu bukan aku, tetapi kupu-kupu yang ada dalam mataku.”
Aku menyatukan kedua alisku sebagai ungkapan kebingungan. Anjum memperhatikan rautku yang penuh dengan pertanyaan. Maka tanpa kuminta ia melanjutkan ceritanya.
“Awalnya makhluk itu tidak percaya, lantas kusuruh ia untuk menengok kedua mataku. Setelah makhluk itu meneropong kedua mataku, serta merta ia menjerit. Aneh sekali, bukan? Aku baru tahu kalau ternyata makhluk itu benci segala jenis keindahan yang ada di alam ini, termasuk kidung-kidung yang sering kunyanyikan. Makhluk itu terlihat begitu gerah, maka tak lama-lama, ia segera mencongkel mataku dan membakar kupu-kupu itu.”
“Kamu membiarkan kupu-kupu itu mati?”
“Kakak tenang saja. Kupu-kupu itu tak pernah mati, hanya saja ia berhamburan ke taman yang mungkin lebih luas dan lebih indah dari mataku. Dan yang paling penting, dengan pita suaraku ini, aku masih bisa mengundang mereka. Kakak tahu? Sekarang kupu-kupu itu menjadi lebih indah dari sebelumnya. Ada kekuatan yang telah mengubah sayap-sayap mereka yang rapuh dengan sutera bermanik yakut. Kalau kakak mau, aku akan mengundang kupu-kupu itu, sekarang.”
“Aku senang dengan kabar itu. Tapi kau…. Kau kini harus melihat dengan sebatang tongkat.”
“Hai, ada hal yang masih belum saya jelaskan pada kakak. Tentang pengelihatan saya ini. Sekarang saya bisa melihat banyak hal tanpa mata, dan semuanya terasa lebih jelas.”
“Kamu… Ah, seperti mimpi saja. Kamu menghayal.” Aku mengabaikan ceritanya.
“Kakak tidak percaya?”
“Aku bukan tidak percaya? Aku hanya…”
“Baiklah, tapi bagaimana kalau sekarang saya bisa melihat semut rang-rang yang merangkak di balik kerah baju kakak.”
Kali ini aku merasa lebih bodoh dari biasanya, tak bisa memahami ungkapan-ungkapan gadis kecil itu. Tiba-tiba kurasakan ada cubitan kecil di tengkukku. Setalah kuraba-raba aku mendapati seekor semut rang-rang hampir tercitas di sana.
Aku merasa semakin bodoh dan linglung. Aku ingin minta penjelasan lebih, namun, lagi-lagi gadis kecil itu membungkam mulutku dengan eufoni surganya. Ia terus menyanyi sepanjang perjumpaan kami dalam mimpi itu, hingga aku terperanjat saat alam sadar menarikku tiba-tiba ke sisinya yang kasar.
Aku tergagap. Wajahku basah oleh keringat. Malam mengaum tepat di puncaknya. Aku berjalan limbung mendekati bibir balkon. Kidung itu masih seperti tertinggal di kepalaku. Mengiang-ngiang seperti kumbang. Saat kutengadahkan wajah ke langit, aku seperti kembali bermimpi, aku melihat gugusan bintang berjajar-jajar, sumringah seperti kelopak bunga yang sedang mekar.
Note:
[1] Petikan kasidah Burdah karya Al-Bushiry